HIDUP YANG TIDAK PERNAH DIRENUNGI, TIDAK LAYAK DIPERJUANGKAN*
*Socrates (470 SM - 399 SM)
Saya
mengutip perkataan perkataan Socrates sebagai judul dari tulisan ini, karena
ya, itu salah satu quotes yang paling
teringat. Hum, entah ingin mulai dari mana. Yang jelas, materi kemarin terasa
sekali berat(?)-nya. Haha, bukan karena disuruh berhitung bilangan berpangkat,
melainkan karena kita diajak berpikir secara mendalam.
Misalnya
saja, di awal materi kami—para GoP ditanya, “Yang mana yang dimaksud Wiwi?”, “Namamu
itu melekat pada apa?” Jleb. Saya sih memang sering mendengar pertanyaan ini
dari orang-orang yang interest dengan
filsafat. Tapi sejujurnya, saya malas membahasnya. Mencari tahu Wiwi itu “apa”-nya
dari saya, terus kenapa saya hidup, saya bertuhan karena betul-betul yakin atau
nurut kepercayaan orang tua.. dan banyak pertanyaan lain, yang apa yah? Mengjengkelkan?
Itu seperti Kau setiap hari melewati Jalan Borong Raya, lalu kau ditanya, Borong itu apa?
Haha. Sampai
kemudian pemateri mengutip perkataan itu. “Hidup
yang tidak pernah dipikirkan, direnungi, direfleksikan.. ialah hidup yang tidak
layak dijalani, tidak pula layak diperjuangkan.”
Oke,
menyambung pertanyaan di awal tadi, sebenarnya yang dilekati oleh nama kita itu
jiwa, raga, atau ruh kita? Tentu banyak yang tahu, sudah pasti itu bukan raga.
Sebab, bila tangan terpisah dari persendiaannya pun nama kita masih dipanggil
secara utuh. Jadi jiwakah? Atau ruhkah?
Dan
jawabannya ialah… jiwa :)
Filosifinya
bisa kita lihat pada ponsel yang sedang mengisi daya. Daya listrik dari colokan
ataupun power bank adalah ruh, yang
Tuhan berikan kepada manusia, yang bersifat sama (kita tidak mengenal ada
listrik baik ataupun jahat kan?). Dan hakikatnya, ruh yang diberikan Tuhan itu
sifatnya baik. Tapi kemudian, ketika dia masuk di ponsel kita (baca: raga),
listrik —yang tersimpan di dalam baterai— itu digunakan untuk kepentingan yang
berbeda-beda. Ada yang lebih banyak untuk social
media, foto dan video, atau menuliskan notes.
Begitulah
kira-kira jawabannya. Ruh adalah sesuatu yang ditiupkan Tuhan kepada kita
hingga kita bisa menjalani kehidupan. Sementara jiwa, ialah semacam
daya/gerakan yang menggerakkan gerakan itu sendiri, kata Platon. Gerakan
menolong, membentak, memberi…
Ya, seseorang dikatakan berjiwa sosial tinggi,
ketika dia peduli dan senang menolong sesamanya. Kita tidak mengatakan beruh (?)
sosial bukan? Lagi pula, saya pernah membaca kisah yang diintisarikan dari Al-Qur’an.
Katanya, sebelum setiap ruh ditiupkan kepada bayi sesaat setelah mereka lahir, mereka
ditanya oleh Allah SWT: bukankah Aku ini
Tuhanmu? Lalu mereka menjawab: Benar
(Engkau adalah Tuhan kami) dan kami menjadi saksi. Tapi pada kenyataannya
ada kan yang mengikari janji? Maka itu sudah pasti bukan salah ruhnya (meskipun
saya juga tidak bilang salah jiwanya hehe). Pembahasan seperti ini belum pantas
saya bawakan. Saya masih harus belajar, dan jangan sampai saya sendiri juga
salah kaprah.
Jadi,
setelah itu kami disuguhkanlah lagu Never
Enough, sebagai pengantar untuk membahas jiwa. Bahwa jiwa manusia, selalu
tidak akan pernah puas meskipun katanya sudah membawa seluruh bintang di
langit, memiliki menara emas, bahkan ketika tangannya sudah menggenggam dunia.
Hmm. Is it really?
Yups.
Ternyata menurut ilmu filsafat, gerak jiwa itu ada tiga. Pertama, gerakan
diagrafma ke bawah, yang selalu ingin memenuhi kebutuhan hidup seperti makan,
minum, pakaian, papan. Kalau kasarnya sih, pikiran gerak ini selalu bersifat
material pokoknya bagaimana caranya supaya bisa hidup lagi besok tanpa rasa
lapar dan tidak kesusahan. Nama geraknya Ephitomea.
Gerak inilah yang dipakai oleh para manusia puba/primitif dalam bertahan hidup,
yang kalau dibawa ke masa sekarang itu, ibarat para pengusaha, pedagang, atau
orang-orang yang mengandalkalkan barang dan tenaganya dalam mencari uang.
Kedua,
gerakan di atas diagrafma sampai sebelum kepala (eh), yang disebut Thumos. Gerak ini cenderung ke arah gentlemen-nya seseorang: sifat ingin
melindungi, tolong-menolong, patriotisme, solidaritas, dan sejenisnya lah. Supaya
lebih mudah dipahami, ingat saja tentara. Karena mereka-mereka yang gerak Thumos-nya dominan kemungkinan akan
mengambil profesi itu. Bagi mereka, kaya bukanlah prioritas asalkan mereka memiliki
harga diri di mata orang, yang salah satu caranya ialah menjadi pejuang.
Ketiga,
namanya Logisticon, gerak pada area
kepala (baca: otak). Tanpa dijelaskan pun pasti banyak yang bisa menebak, bahwa
gerak ini sangat mengandalkan akal, pokonya apa-apa harus dipikir dulu. Baik-buruknya,
untung-ruginya, semua sebisa mungkin logis bagi gerak ini. Yang dicontohkan
dari seseorang yang berkecenderungan terhadap gerak ini ialah politikus dan
para akademisi.
Secara
umum, semua manusia punya ketiga gerak ini. Hanya saja, ada yang porsinya lebih
banyak, lebih sedikit, bahkan ada yang membawanya ke jalan yang salah. Coba
perhatikan gambar kereta kencana di bawah ini:
Si pengendali
kereta itu ibarat Logisticon
Si kuda
hitam ibarat Thumos
Sedangkan kuda
putih ibarat Ephitomea
Untuk dapat
berjalan, kereta kencana tentu membutuhkan ketiga elemen itu. Hanya saja
kelihatan, bahwa yang mengendalikan itu si Logisticon.
Artinya, jika otak atau akal kita sudah niatnya yang bukan-bukan, yah kedua
gerak lainnya akan nurut. Jadi meskipun punya jiwa patriotisme tinggi, bisa
saja mengkhianati tanah air. Atau yang tadinya niat mencari penghasilan karena
butuh, mulai disisipi dengan keinginan lain akibat kepentingan dari si Logisticon ini.
So,
kesimpulannya semua harus seimbang. Jangan memberi ‘makan’ lebih banyak pada
satu jiwa saja. Dan yang lebih penting, kendalinya ada di pikiran kita, di akal
kita. Percayalah, bahwa ketidakseimbangan antar-ketiga jiwa bisa membawa
masalah yang runyam.
Misalnya
ketika dwifungsi ABRI berlaku pada Orde Baru dulu, dimana oang-orang yang
memiliki jiwa patriot (baca: tentara) diperbelohkan juga untuk menduduki
jabatan politik. Atau ketika yang diangkat sebagai pemimpin adalah yang jiwa Ephitomea-nya tinggi. Tentulah besar
kemungkinan akan terjadi eksploiatasi (dalam konteks sumber daya), termasuk
nepotisme oleh mereka yang otoriter dan ingin terus menguasai.
Haha, ilmu
saya belum cukup untuk mengkritiki sebuah rezim. Saya hanya bisa berkata,
sungguh sayang apabila mereka yang tidak paham bagaimana menyeimbangkan ketiga
gerak ini diangkat menjadi pemimpin, apalagi yang memanfaatkan Logisticon-nya di jalan yang salah.
Politik licik namanya. Tapi ya sudahlah. Kita tidak ingin membicarakan itu
sekarang.
Akhirnya,
bagaiamana cara menyeimbangkan ketiganya?
Keseimbangan
dari Logisticon, Thumos, dan Ephitomea disebut dengan kondisi equilibrium. Dan untuk mencapai itu,
inilah yang harus kita lakukan pada setiap gerak:
1. Ephitomea, timbulkan sifat “Ugahari” atau kesadaran jiwa untuk
merasa cukup, tidak berlebih-lebihan.
2. Thumos, kendalikan emosi, harus berani dalam menyampaikan
kebenaran, daripada iming-iming solidaritas. Misalnya ketika teman yang kita sayangi
(bisa juga kakak, ayah, atau ibu) melakukan kesalahan (narkoba, mencuri/korupsi,
atau membunuh), kita harus berani menyampaikannya. Baik itu kepada si pelaku,
maupun kepada pihak-pihak yang harus tahu perbuatan pelaku. Tidak dibenarkan
untuk menghiraukannya hanya karena merasa kita solid. Justru teguran itulah
bentuk rasa sayang kita kepadanya.
3. Logisticon, kuncinya ialah
wisdom. Iya, akal kita harus bijak, karena dialah yang mengendalikan dua
gerak lainnya. Bijak ini beda loh dengan pintar. Socrates bilang, “the only true wisdom is in knowing that you
know nothing.” Ya, seringkali orang pintar lupa bagaimana caranya menjadi
bijak—rendah hati, karena mereka pikir sudah mengetahui banyak.
Equilibrium ini pun muaranya ialah justice pada setiap diri manusia. Mereka akan tahu bagaiamana
bersikap dalam interaksi dengan golongan apapun dan pada strata sosial-ekonomi
manapun. Tidak berlebihan, cukup ambil jalan tengahnya saja..
Dari sini
pun kita bisa tahu, bahwa akar dari segala konflik sebenarnya, bahwa
masing-masing orang membawa self interest-nya
ke ranah interaksi antar-manusia. Self
interest di situ bisa merujuk ke salah satu dari tiga gerak jiwa tadi.
Apakah karena dia ingin berkuasa sepenuhnya, ingin membela kelompoknya, atau
meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Masing-masing kita pasti bisa mengukur
sendiri.
Akhir kata,
membahas sedikit pandemi yang nampaknya belum akan berakhir ini, saya ingin
mengucapkan terima kasih bagi Pembaca yang Budiman (eh sudah lama tidak
menyebut ini) yang berusaha sebisa mungkin untuk tetap di rumah, meskipun itu
berat. Ya, entah karena adanya self
interest (kecuali terpaksa) atau
memang karena ketidaksadaran, masih banyak orang-orang yang tetap bepergian
walau urgensinya tidak penting-penting amet.
Tapi ya sudahlah, kita tidak punya kuasa atas gerak jiwa orang lain, kan?
PS: setiap gambar yang ada di atas merupakan beberapa slide power point dari KITA Bhinneka Tunggal Ika
(Ini adalah judul asli dari materi PLC #8)
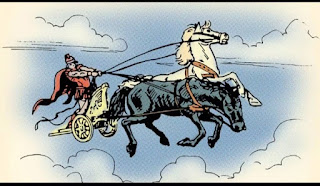





Bahas mobel lejen dong min🙏
BalasHapus